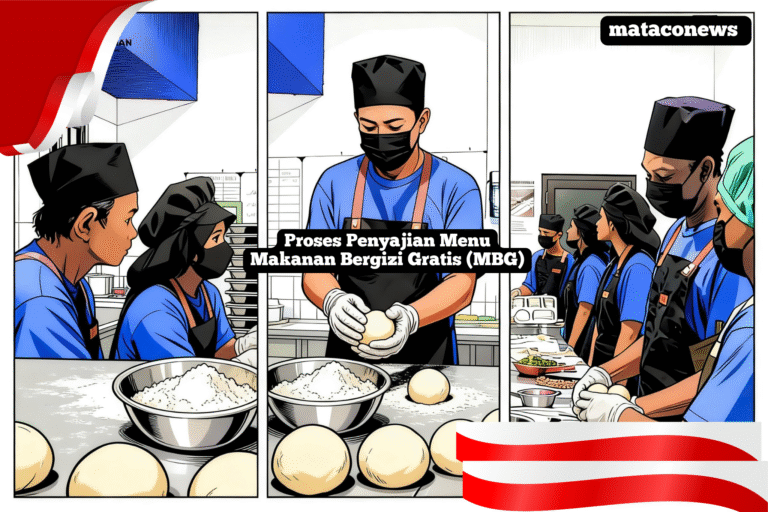Di salah satu rumah papan berdiri sepasang suami-istri sederhana: Muhammad Basri alias Mat Basur dan Samiyem yang akrab dipanggil Siyem. Ia pedagang itik atau basur di pasar Wagean sehingga namanya dikenal sebagai Mat Basur, sementara istrinya ikut bersih-bersih ikan di pelelangan. Mereka tak punya tabungan banyak, tapi punya moral dan rasa saling bantu yang tinggi. Mereka bukan siapa-siapa di peta politik. Tapi mereka adalah fondasi negeri ini. “Tangisan bayi Mat Acon lahir dari bantaran sungai, bukan dari gedung rumah sakit megah. Saat negara datang dengan slogan, rakyat kecil sudah lebih dulu bergerak menyelamatkan nyawa. Inilah wajah republik dari pinggiran Cilacap.” Kala itu di penghujung tahun 1995, suasana masih terasa dingin seusai hujan turun semalaman di Tegal Kamulyan, kampung kecil di pinggiran Cilacap. Kabut tipis melayang di atas sungai Kaliyasa PPC, menyelimuti deretan rumah reyot dari papan, seng, dan triplek bekas. Bau amis ikan dan air sungai menyusup ke hidung, bukan sebagai gangguan, tapi sebagai tanda hidup. Di sini, tidak ada open space dan taman taman, tidak ada jalan mulus, apalagi Mall dan Pusat perbelanjaan. Yang ada hanya suara ember diseret dan jaring ditarik nelayan. Inilah wajah paling jujur dari republik ini — pinggiran yang sering terlupakan. Kampung ini hidup dari peluh rakyat kecil. Para nelayan dan buruh bangun sebelum fajar, bukan untuk mengejar cita-cita besar, tapi sekadar bertahan hidup. Negara jarang hadir di sini. Ia hanya mampir lewat baliho, brosur program kesehatan, dan papan slogan “Pelayanan Cepat & Setara untuk Semua”. Tapi saat rakyat benar-benar butuh pertolongan, slogan itu sering tinggal tulisan. Pagi itu, ketika udara masih basah dan langit belum terang, perut Siyem mules kuat. Kandungannya sudah cukup bulan. Saat membersihkan ikan, Siyem terpeleset saat menjunjung sekeranjang ikan karena lantai licin sehingga ketubannya pecah di lantai pelelangan. Orang-orang di sekitar panik. “Waduh, Siyem arep lahiran kiye!” seru tetangga. “Gagean telpon Mat Basur, cepet!” teriak yang lain Mat Basur, yang sedang jualan di pasar begitu menerima kabar itu, segera pergi mengemasi dagangan dengan motor honda Tuyul butut keluaran tahun 70-an . Orang kecil tidak punya kemewahan, waktu apalagi pilihan — mereka hanya bisa bergerak sendiri. Ketika tiba, ia mendapati wajah istrinya pucat, napas tersengal, dan mata warga penuh cemas. Mereka mencari kendaraan. Di pojok parkiran, pemilik mobil Panther Hi Grade Type terbaru warna merah maron, dikenal sebagai juragan ikan pemilik puluhan kapal menolak: “Maaf ya… mobil saya baru. Saya gak bisa kalua dipakai buat ngangkut orang kayak gitu. Bau amis.” Kalimat singkat itu tajam, menancap dalam. Di negeri ini, cat mobil bisa lebih berharga dari nyawa ibu yang hendak melahirkan. Ketika semua panik, suara mesin mobil pikap tua terdengar. Babah Acon, tengkulak ikan paruh baya, datang. “ Ayuh digotong nang aring pikapku. Ora usah mikir mambu amis. Wong urip kudu nulungi wong urip,” ujarnya pelan namun tegas. “ Urip kae kudu urup “. Tikar lusuh dijadikan tandu darurat. Warga bersama-sama menggotong Siyem ke atas pikap. Di bak belakang, Mat Basur menggenggam tangan istrinya erat-erat. (Dalam hati dia berjanji): “Ngesuk nek aku nganti nduwé mobil, ora bakal tek gunakna nggo nggaya – nggayaan. Tapi bakal tek nggo nulungi wong sing agi rekasa kaya aku, men pada nyontoh Babah Acon sing nulungi bojoku siki.” Mobil pikap itu melaju membelah jalan kampung yang becek. Dalam keheningan, ada doa yang tidak bersuara, tapi menggetarkan. Pagi itu, ketika udara masih basah dan langit belum terang, perut Siyem mules kuat. Kandungannya sudah cukup bulan. Saat membersihkan ikan, Siyem terpeleset saat menjunjung sekeranjang ikan karena lantai licin sehingga ketubannya pecah di lantai pelelangan. Orang-orang di sekitar panik. “Waduh, Siyem arep lahiran kiye!” seru tetangga. “Gagean telpon Mat Basur, cepet!” teriak yang lain Mat Basur, yang sedang jualan di pasar begitu menerima kabar itu, segera pergi mengemasi dagangan dengan motor honda Tuyul butut keluaran tahun 70-an . Orang kecil tidak punya kemewahan, waktu apalagi pilihan — mereka hanya bisa bergerak sendiri. Ketika tiba, ia mendapati wajah istrinya pucat, napas tersengal, dan mata warga penuh cemas. Mereka mencari kendaraan. Di pojok parkiran, pemilik mobil Panther Hi Grade Type terbaru warna merah maron, dikenal sebagai juragan ikan pemilik puluhan kapal menolak: “Maaf ya… mobil saya baru. Saya gak bisa kalua dipakai buat ngangkut orang kayak gitu. Bau amis.” Kalimat singkat itu tajam, menancap dalam. Di negeri ini, cat mobil bisa lebih berharga dari nyawa ibu yang hendak melahirkan. Ketika semua panik, suara mesin mobil pikap tua terdengar. Babah Acon, tengkulak ikan paruh baya, datang. “ Ayuh digotong nang aring pikapku. Ora usah mikir mambu amis. Wong urip kudu nulungi wong urip,” ujarnya pelan namun tegas. “ Urip kae kudu urup “. Tikar lusuh dijadikan tandu darurat. Warga bersama-sama menggotong Siyem ke atas pikap. Di bak belakang, Mat Basur menggenggam tangan istrinya erat-erat. (Dalam hati dia berjanji): “Ngesuk nek aku nganti nduwé mobil, ora bakal tek gunakna nggo nggaya – nggayaan. Tapi bakal tek nggo nulungi wong sing agi rekasa kaya aku, men pada nyontoh Babah Acon sing nulungi bojoku siki.” Mobil pikap itu melaju membelah jalan kampung yang becek. Dalam keheningan, ada doa yang tidak bersuara, tapi menggetarkan.
Pagi itu puskesmas kampung baru saja buka. Udara lembab bercampur bau karbol tipis dari lorong sempit. Di depan pintu masuk, spanduk berwarna biru menggantung lemas: “Setiap Warga Berhak atas Pelayanan Kesehatan yang Bermutu.” Huruf-hurufnya besar, tapi wajah petugas di balik meja tidak memantulkan semangat slogan itu. Mat Basur datang tergesa sambil membopong istrinya yang sudah nyaris tak sanggup berdiri. Napas Siyem tersengal, keringat dingin membasahi leher dan pipinya. Ia ingin cepat masuk, tapi langkahnya terhenti di depan meja administrasi. “KTP-nya, sama uang mukanya ya, Pak,” tanya seorang petugas perempuan, suaranya datar, seperti membacakan kalimat hafalan. Mat Basur terdiam sejenak, matanya basah. Ia bukan tak paham prosedur — tapi siapa yang sempat memikirkan KTP saat nyawa istrinya sedang berkejaran dengan waktu? “Lha bojoku kie arep lahiran siki, Bu… ora sempat mikir KTP apa maning nggawa duit..!” jawab Mat Basur, separuh panik, separuh putus asa. “ Tulung lah Bu.. “. Ujarnya setengah memohon Petugas menunduk sebentar, lalu dengan suara pelan tapi kaku, ia melanjutkan: “Kalau gak ada, ya susah Pak… prosedur harus dilengkapi.” Kalimat itu terdengar biasa — tapi bagi telinga Mat Basur, kalimat itu seperti tembok. Tembok yang memisahkan mereka dari pertolongan. Ia menatap sekeliling: tembok puskesmas kusam, kursi plastik reyot, dan spanduk besar yang tiba-tiba terasa seperti lelucon. Dari luar, suara Babah Acon menyahut lirih tapi jelas. “Kie wong lagi antara urip lan mati, deneng malah ditakoni werna werna. Nek kowe gelem mikir nganggo ati, mestine wonge kiye kudu ditulungi disit!” Tegas babah Acon. “ Tulung diwaca maning, aturane wis cetha. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan karo aturan puskesmas ngomong, wong sing butuh pertolongan kudu dilayani. Ora ana aturan wong susah kudu mbayar dhisit nek kahanan darurat.”
Aja kaya kuwe lha mbak “ tukas Babah Acon lagi. “ Tapi ya wis ngeneh pira tek bayar..! “. Petugas menghela napas pelan, seperti orang yang sadar tapi terbelenggu aturan. “Saya ngerti, Pak. Tapi prosedur kami begitu…” jawabnya lirih. “Prosedur ora iso ngalahna nyawa, mbak,” potong Babah Acon pelan, tapi tegas. “Negara nggawe aturan supaya wong cilik urip, udu malah uripe tambah rekasa.” Petugas terdiam, tak lama kemudian meninggalkan kedua orang itu menghampiri seorang Bidan dan bergerak cepat. Dalam situasi genting, suara rakyat kecillah yang mengingatkan negara tentang kewajibannya Dalam kecemasan Mat Basur menggenggam tangan Siyem makin erat. Ia tidak tahu banyak tentang hukum, tapi ia tahu satu hal: kehidupan orang kecil sering ditahan bukan oleh musuh, tapi oleh aturan yang lupa dengan hati. Dengan rasa kasih berbaur rasa cemas dia berbisik mendekat ke telinga istrinya “ Sing sabar ya dik, ditahan sedela. Kiye wis agi arep ditangani “. Sekitar pukul 09.45 pagi. Tangisan bayi laki-laki memecah pagi itu di Cilacap. Bukan tangisan di rumah sakit besar, bukan dalam pelukan dokter berjas rapi. Tangisan itu lahir dari bayi Tempat Pelelangan Ikan kecil di bantaran kali — dari rahim seorang ibu yang tak punya asuransi swasta dan dari keberanian rakyat kecil yang menolak diam. “Namanya siapa, Pak Basur?” tanya bidan lirih. “Hmm.. sapa ya bu ? setengah bergumam Mat Basur balik bertanya. “Jenengé… Muhammad Acon. Iya undangane Mat Acon bae lah,” jawabnya lugu dan lugas. “ Men bisa ngemut jenenge wong sing tau nulungi aku “. Lanjut Mat Basur dengan wajah sedikit tertunduk Bagi Mat Basur waktu itu, nama bukan sekadar nama. Itu merupakan simbol. Nama Babah Acon, yang tanpa seragam dan tanpa gaji negara, bergerak lebih cepat dari sistem pelayanan publik yang seharusnya. Sementara di sudut yang lain, Babah Acon duduk di bangku kayu luar puskesmas, rokok kretek Djarum 76 menyala di tangannya. “Wong cilik kuwe ora butuh belas kasihan,” ujare Babah Acon pelan nanging njedug maring njerone ati. “Negara kuwe jan jane wis nulis aturan sing apik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 53 ayat (2): ‘Pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat harus diberikan kepada siapa pun dan tidak boleh ditolak dengan alasan biaya.’ Tapi nyatane nek wong cilik arep mbutuhna layanan Kesehatan bae kudu rebutan nasib njaluk belas kasihan, artine negara mung ana nang kertas — durung tekan ning ati.” “ Angger kaya kie negara apa jenenge ya “. Dua orang yang turut mengantar hanya mengangguk pelan. Seorang ibu berbisik: “Sing nulungi wong cilik ya wong cilik dewek.” Celetuk seorang wanita paruh baya sesama buruh di TPI bernama Lasmina Tangisan Mat Acon pelan-pelan reda, tapi gema suaranya belumlah hilang. Ia merembes ke hati warga dikampung Tegal Kamulyan — sunyi tapi nyaring — mengingatkan semua orang bahwa di republik ini, rakyat kecil sering jadi barisan pertama saat negara telat datang. Undang-undang boleh ditulis rapi di atas kertas negara, tapi keadilan sejati lahir dari tangan-tangan kotor rakyat pinggiran: dari tikar lusuh, gotong royong, dan keberanian mereka menolak menyerah. Babah Acon mungkin cuma tengkulak ikan, tapi tindakannya lebih cepat dari sistem. Ia bukan pejabat, bukan aparat, bukan program. Ia hanya manusia biasa yang memilih tidak diam. Dan di situlah letak keadilan paling murni — saat kemanusiaan melampaui birokrasi. Mat Acon lahir bukan hanya sebagai bayi dari rahim Samiyem, tapi sebagai simbol tentang siapa sebenarnya yang menopang republik ini: wong cilik sing tansah urip nganggo roso lan gotong royong. Suara tangisnya adalah pesan yang lebih lantang dari pidato pejabat: “Negara harus hadir bukan hanya dalam teks hukum, tapi dalam detik-detik genting kehidupan rakyatnya.” (Amin/matacon)